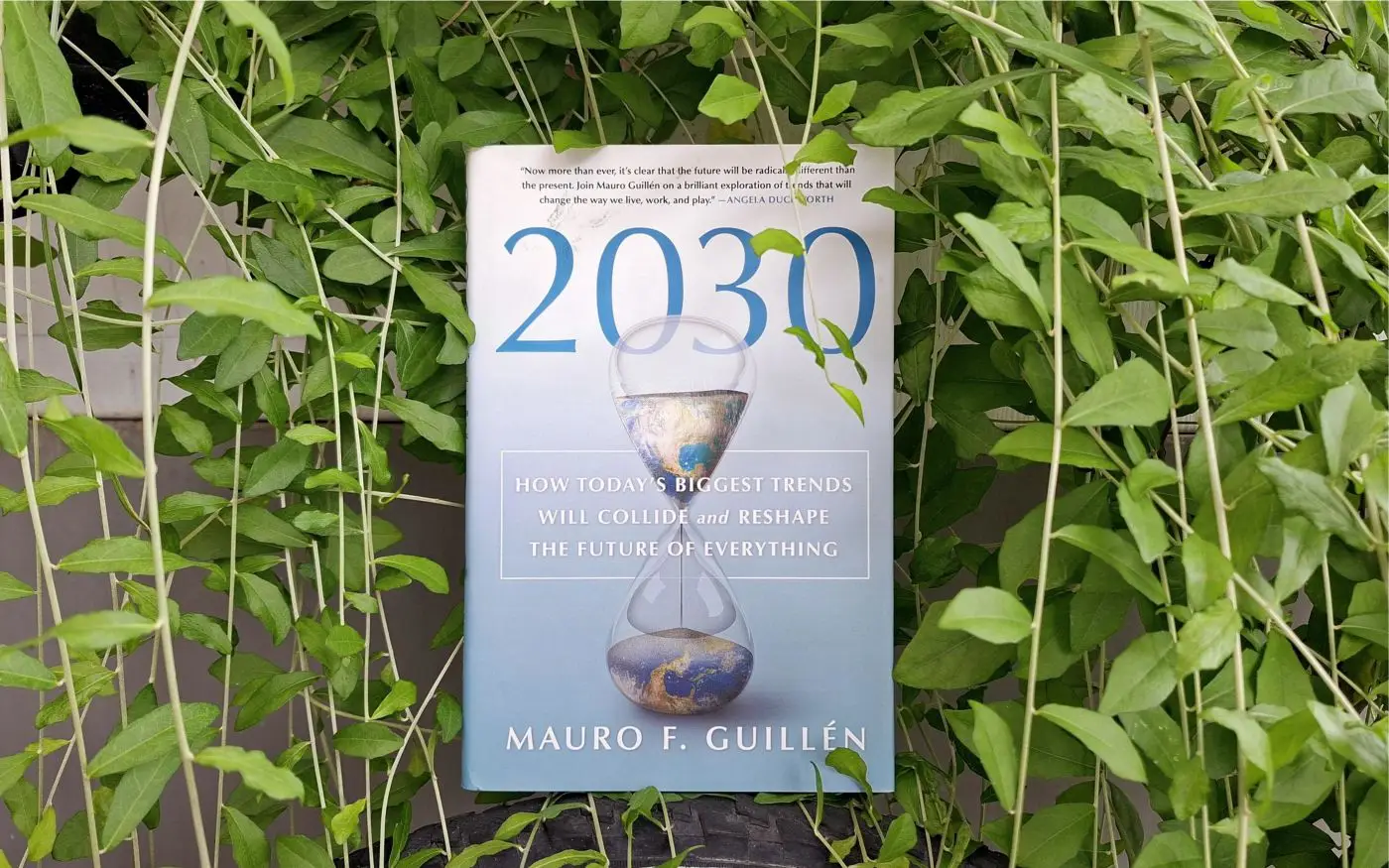Bayangkan dunia di mana populasi lansia lebih banyak dari generasi muda, Afrika menjadi pasar raksasa baru, dan wanita menguasai mayoritas kekayaan global. Sebuah dunia yang sama sekali tidak kita kenal, tetapi hanya berjarak lima tahun dari sekarang.
Seperti itulah gambaran masa depan yang ditawarkan Mauro F. Guillen dalam bukunya yang provokatif, 2030: How Today’s Biggest Trends Will Collide and Reshape The Future of Everything. Guillen, seorang profesor manajemen terkemuka, bukanlah seorang peramal. Ia seorang pemeta tren yang brilian, yang menyatukan titik-titik data demografi, teknologi, ekonomi, dan geopolitik menjadi sebuah peta navigasi yang tak ternilai untuk dekade mendatang. Buku ini bukan sekadar daftar prediksi; ia adalah seruan untuk mengubah pola pikir kita. Namun, ketika peta masa depan global ini kita sandingkan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 dan realitas kebijakan kita hari ini, sebuah kegelisahan mendalam muncul: Apakah Indonesia sedang berlayar menuju visi emas itu dengan peta yang benar, atau justru tersesat dengan peta dari masa lalu?
Guillen memaparkan tujuh “tabrakan besar” tren yang akan mendefinisikan ulang segalanya pada 2030. Beberapa yang paling menonjol adalah: (1) Revolusi Silver (Penuaan Populasi Global) yang akan menggeser kekuatan ekonomi dari Barat ke Timur, tetapi juga menciptakan krisis pensiun dan tenaga kerja; (2) Bangkitnya Kelas Menengah Perkotaan di Asia dan Afrika, dengan selera konsumsi yang sangat berbeda; (3) Era Kepemilikan yang Berakhir, digantikan ekonomi berbagi dan berlangganan; (4) Bangkitnya Teknologi yang Memperkuat (AI, bioteknologi) yang akan mengubah pekerjaan secara radikal; dan (5) Perempuan sebagai Pemilik Mayoritas Kekayaan Global. Kekuatan buku ini terletak pada cara Guillen merajut tren-tren yang tampak terpisah ini menjadi sebuah narasi koheren tentang dunia yang terbalik—di mana asumsi-asumsi lama tentang pertumbuhan, pasar, dan kekuatan akan runtuh.
Lantas, di manakah posisi Indonesia dalam peta dunia 2030 ini?
Dari segi demografi, Indonesia masih memiliki bonus demografi yang menjadi dasar Visi Indonesia Emas 2045. Ini adalah aset tak ternilai di tengah dunia yang menua. Namun, Guillen mengingatkan bahwa bonus demografi bukan jaminan. Ia hanya akan menjadi “bom waktu” jika tidak diiringi dengan investasi besar-besaran pada kualitas manusia: pendidikan yang relevan (STEM, literasi digital, critical thinking), kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja bernilai tinggi. Di sinilah letak kritik pertama: Apakah transformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi kita cukup cepat dan visioner untuk menciptakan generasi yang siap bersaing di ekonomi 2030 yang berbasis pengetahuan? Atau kita hanya akan menghasilkan lebih banyak tenaga kerja murah yang kalah bersaing dengan otomasi?
Dari sisi ekonomi, Indonesia berpotensi menjadi bagian dari “kelas menengah perkotaan baru” Asia. Namun, Guillen menekankan bahwa konsumen masa depan adalah konsumen yang sadar keberlanjutan, digital, dan mengutamakan pengalaman atas kepemilikan. Apakah industri nasional kita—yang masih banyak berkutat pada komoditas dan manufaktur tradisional—sudah berinovasi untuk memenuhi selera ini? Ketergantungan pada ekspor sumber daya mentah justru membuat kita rentan dalam dunia yang semakin menghargai ekonomi sirkular dan energi terbarukan. Kebijakan “downstreaming” perlu dipercepat dan diperdalam agar tidak sekadar menjadi ekspor produk setengah jadi, tetapi menciptakan merek dan teknologi sendiri.
Aspek sosial-politik paling mengkhawatirkan. Guillen berbicara tentang dunia di mana keragaman, kesetaraan gender, dan kelincahan beradaptasi adalah kunci. Namun, narasi sosial-politik Indonesia belakangan ini sering diwarnai oleh polarisasi identitas, yang berisiko menyia-nyiakan energi bangsa untuk konflik internal alih-alih fokus pada persaingan global. Inklusivitas—terutama pemberdayaan perempuan sebagai potensi ekonomi raksasa yang disorot Guillen—masih terbentur tembok budaya dan kebijakan yang belum maksimal mendukung partisipasi penuh perempuan di ekonomi dan politik.
Membaca *2030* karya Guillen membuat saya tersadar: jarak antara mimpi dan realitas sedang dipertaruhkan dalam setiap kebijakan kita hari ini. Kesiapan Indonesia dipertanyakan pada beberapa front kritis:
- Kesiapan Infrastruktur Digital dan Hijau: Apakah pembangunan infrastruktur fisik kita sudah seiring dengan pembangunan infrastruktur digital (5G, data center, keamanan siber) dan energi terbarukan yang menjadi tulang punggung ekonomi 2030?
- Agilitas Birokrasi dan Regulasi: Dunia 2030 bergerak cepat. Bisakah birokrasi yang lamban dan regulasi yang kaku berubah menjadi enabler untuk inovasi startup, ekonomi kreatif, dan investasi hijau?
- Mindset Kepemimpinan: Apakah para pemimpin di bisnis dan politik kita memiliki keberanian untuk berpikir melampaui siklus politik 5 tahunan dan komoditas jangka pendek, menuju investasi jangka panjang pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan manusia?
Visi Indonesia Emas 2045 bisa jadi adalah tujuan yang tepat. Namun, untuk mencapainya, tidak bisa lagi berjalan dengan cara-cara lama. Kita harus lari, dan lari ke arah yang benar—yaitu ke arah dunia yang digambarkan Guillen: dunia yang inklusif, digital, berkelanjutan, dan didorong inovasi. Tantangan terbesar kita bukanlah sumber daya, tetapi keberanian untuk bertransformasi dan kesungguhan untuk menjadikan bonus demografi sebagai “generasi emas” yang mampu memenangkan persaingan di dunia 2030 yang penuh disrupsi. (*)