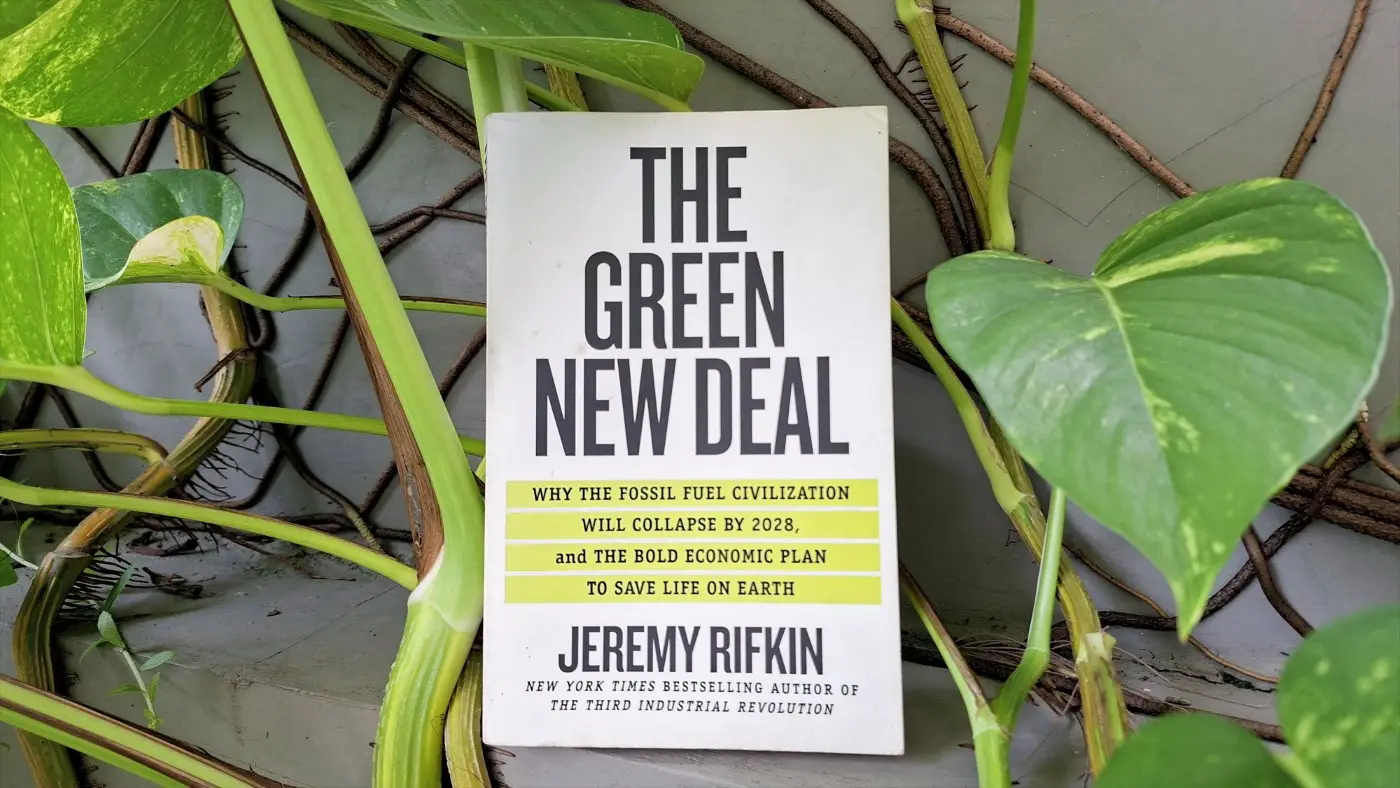Membaca buku The Green New Deal karya Jeremy Rifkin ini membuat saya merenung dan berpikir bahwa buku ini lebih dari sekadar manifesto lingkungan. Buku ini adalah cetak biru sistematis yang menyambungkan titik-titik antara revolusi teknologi digital, energi terbarukan, dan mobilitas listrik menjadi sebuah ekosistem ekonomi baru—”Internet of Things” berbasis energi hijau. Buku ini menjadi semacam peta yang tidak hanya menunjukan jalan keluar dari bencana iklim, tetapi juga membuka era kemakmuran ekonomi baru yang inklusif. Itulah janji yang dihadirkan Rifkin dalam bukunya yang judul lengkapnya adalah The Green New Deal: Why the Fossil Fuel Civilization Will Collapse by 2028, and the Bold Economic Plan Is Required to Save Life on Earth. Di tengah panasnya krisis iklim yang semakin nyata, buku Rifkin bagai petunjuk teknis dan filosofis yang mendesak. Terutama bagi Indonesia, yang janji transisi energinya masih terperangkap dalam jaring kebijakan yang ambigu dan keberpihakan nyaris mutlak pada energi fosil.
Rifkin membangun argumennya di atas tiga pilar revolusi industri yang menurutnya sedang bertemu dan saling memperkuat: revolusi komunikasi (Internet), revolusi energi (Energi Terbarukan Terdistribusi), dan revolusi mobilitas/logistik (Kendaraan Listrik dan Otonom). Konvergensi ketiganya, dipicu oleh biaya energi matahari dan angin yang turun drastis serta kecerdasan buatan, akan menciptakan “Internet of Energy”. Dalam ekosistem ini, setiap rumah, pabrik, dan kendaraan menjadi produsen dan konsumen energi yang saling terhubung, menggeser paradigma dari sistem energi terpusat berbasis fosil (oligopolistik) ke sistem terdistribusi yang demokratis. Rifkin dengan yakin—dan sedikit kontroversial—memprediksi keruntuhan peradaban bahan bakar fosil akan dimulai pada 2028. Prediksi ini bukan tanpa dasar; ia menunjukkan tren penurunan biaya kurva-S yang sama yang pernah menghancurkan industri film dan telepon kabel.
Buku ini berhasil karena menggabungkan visi besar dengan detail praktis. Rifkin tidak hanya berbicara tentang panel surya, tetapi tentang restrukturasi infrastruktur nasional, penciptaan “pekerjaan hijau” yang masif, dan pendanaan melalui obligasi hijau. Kekuatannya terletak pada kemampuannya merangkai isu-isu yang sering dipisahkan—iklim, ekonomi, keadilan sosial—menjadi satu narasi kohesif tentang kelangsungan hidup dan peluang.
Seperti biasanya saat saya membaca sebuah buku, saya selalu berusaha menempatkan konteks narasinya dalam kondisi di Indonesia. Di sinilah relevansi dan ironi bagi Indonesia menjadi begitu tajam. Indonesia memiliki semua bahan baku untuk mewujudkan mimpi Rifkin: potensi energi matahari, angin, panas bumi, dan hidung yang sangat besar; pasar digital yang masif; serta komitmen politik di atas kertas untuk mencapai Net Zero Emission 2060. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebuah pemerintahan yang “tidak serius” atau paling tidak, sangat ambivalen.
Pertama, komitmen yang dibajak oleh kepentingan fosil. Di tengah sorotan global, Indonesia justru menggandakan ekspansi energi batu bara melalui program “co-firing” PLTU dengan biomassa (yang justru berisiko deforestasi) dan Carbon Capture and Storage (CCS) yang mahal dan belum teruji. Kebijakan ini lebih mirip upaya memperpanjang umur industri batu bara daripada transisi yang jujur. Kedua, regulasi yang menghambat. Peraturan tentang energi terbarukan, seperti tarif listrik EBT yang tidak menarik bagi investor swasta dan birokrasi yang berbelit, menunjukkan ketiadaan kemauan politik untuk menciptakan pasar yang kompetitif. Ketiga, kurangnya visi sistemik ala Rifkin. Fokus pemerintah masih sangat sektoral—membangun panel surya atau pabrik baterai—tanpa desain besar untuk mengintegrasikannya menjadi smart green grid nasional yang terdistribusi. Alih-alih memanfaatkan pulau-pulau kecil sebagai laboratorium energi terbarukan mandiri, solusi utama masih berpusat pada PLTU dan mega-proyek yang rawan korupsi.
The Green New Deal karya Rifkin, pada akhirnya menjadi inspirasi sekaligus cermin yang mempermalukan bagi pemerintah Indonesia. Buku ini menunjukkan bahwa transisi energi bukanlah beban, melainkan peluang emas untuk membangun perekonomian yang lebih tangguh, mandiri, dan berkeadilan. Ia menawarkan peta yang jelas. Sayangnya, pemerintah Indonesia tampak lebih nyaman membaca peta lama yang menuju jurang—peta yang dikepung oleh kepentingan korporasi batu bara dan oligarki energi, serta dibutakan oleh pendapatan ekspor jangka pendek dari komoditas kotor.
Melihat pada konteks Indonesia, saya merasa Rifkin cenderung optimistis-sentralistik, seakan-akan logika pasar dan teknologi akan dengan sendirinya mengatasi semua hambatan politik dan kekuatan korporasi raksasa fosil yang sudah mapan. Ia kurang mengakomodasi pertarungan kekuasaan yang keras dan ketergantungan path-dependency yang mengikat banyak negara.
Namun, Rifkin telah memberikan peta. Pertanyaannya sekarang: Apakah Indonesia memiliki keberanian politik untuk membuang peta usang dan memulai perjalanan hijau yang sesungguhnya, atau akan tetap menjadi penonton yang tertinggal dalam perlombaan menentukan masa depan bumi? Waktu untuk menjawabnya semakin pendek. (*)