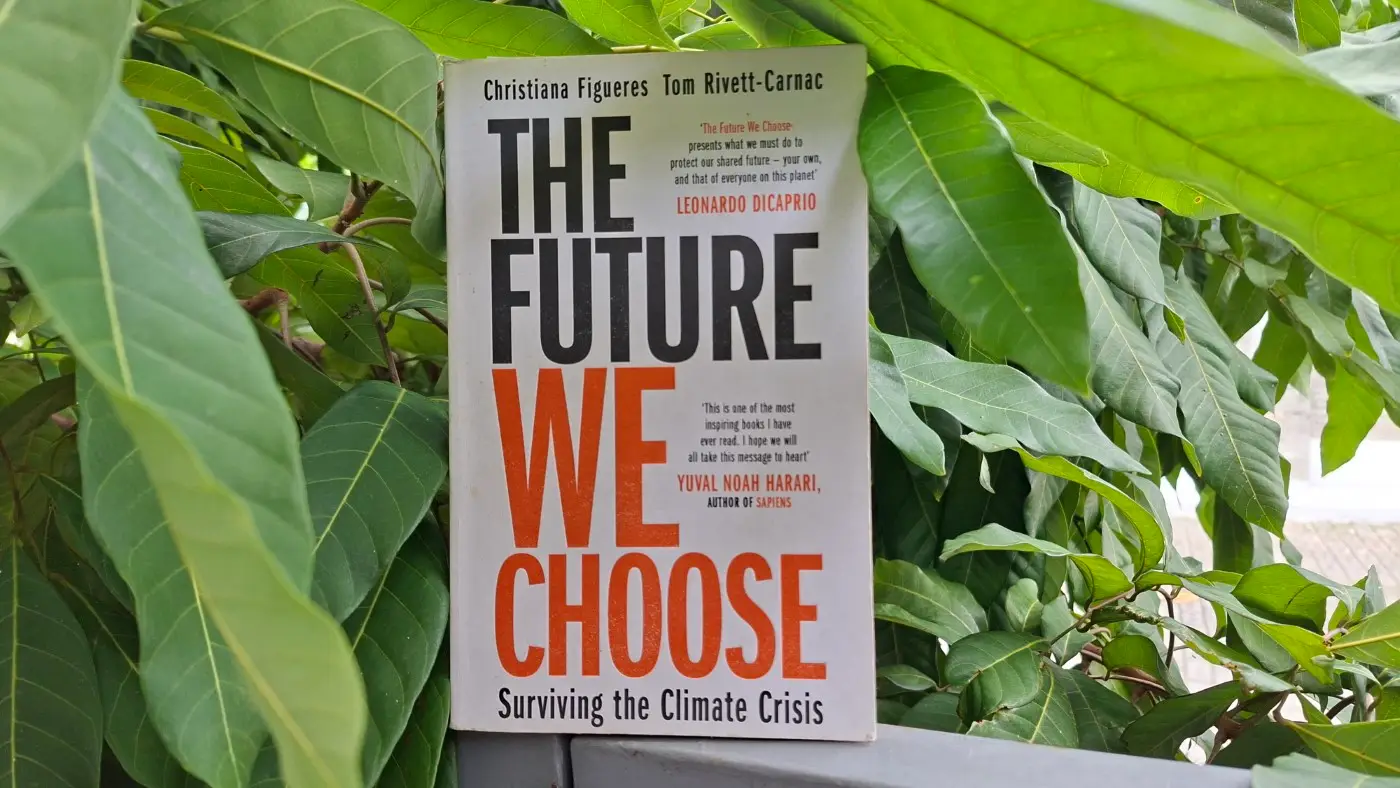Banjir bandang dan tanah longsor yang kembali melanda Sumatera di akhir bulan November 2025, merenggut nyawa, menghanyutkan rumah, dan menyisakan nestapa, bukan sekadar “bencana alam”. Itulah secuil wajah masa depan yang kita pilih sehari-hari. Sebuah masa depan yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan kebijakan pembiaran, konsesi lahan yang gelap, dan ketamakan jangka pendek. Saya jadi teringat buku yang pernah saya baca, judulnya The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis karya Christiana Figueres dan Tom Rivett-Carnac. Keduanya adalah arsitek utama Perjanjian Paris 2015. Dalam buku ini mereka tidak hanya menyajikan data suram krisis iklim, tetapi lebih penting: sebuah peta jalan psikologis dan politis untuk memilih masa depan yang layak dihuni. Buku ini menjadi cermin yang sangat tajam bagi Indonesia: akankah kita terperosok ke dalam “Masa Depan 3°C” yang penuh bencana, atau memiliki keberanian kolektif untuk membangun “Masa Depan 1.5°C” yang berkelanjutan?
Figueres dan Rivett-Carnac menyajikan narasi dengan struktur yang brilian: mereka menggambarkan dua dunia pada tahun 2050. Dunia pertama adalah neraka yang terinkarnasi—udara beracun, kota-kota tenggelam, konflik pangan, dan kepunahan massal. Dunia kedua adalah visi yang dapat dicapai—masyarakat yang berhasil melalui transisi besar, hidup harmonis dengan alam, dengan energi bersih dan ekonomi sirkular.
Buku ini tidak banyak mengumbar data-data (yang sudah banyak kita dengar) tetapi lebih pada pendekatannya yang membumi. Mereka mengakui bahwa krisis iklim adalah krisis psikologis—dipicu oleh ketakutan, kelumpuhan, dan keputusasaan. Karena itu, mereka menawarkan “Pikiran untuk Bertindak”: sepuluh sikap mental (seperti Ketabahan, Optimisme, dan Kesadaran Penuh) yang harus dipupuk, dilengkapi dengan sepuluh aksi konkret di tingkat sistemik, dari politik hingga teknologi.
Bagi kita yang hidup dan tinggal di Indonesia, gambaran “Masa Depan 3°C” bukanlah fiksi ilmiah bagi masyarakat di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak di Sumatera atau Kalimantan. Ia adalah realitas harian yang diperparah oleh sebuah sistem yang sakit. Pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan sawit monokultur dan tambang, sering kali melalui izin yang dikeluarkan dengan cara yang meragukan, adalah motor penggerak deforestasi dan degradasi lingkungan. Hutan yang berfungsi sebagai penahan air dan penyangga ekosistem, diubah menjadi ladang komoditas ekspor dan kubangan tambang. Banjir dan longsor yang kita saksikan adalah buah dari pilihan ekonomi tersebut. Kebijakan moratorium yang ada sering kali bagai pisau tumpul, dikelilingi oleh loophole dan penegakan hukum yang lemah.
Di balik izin-izin itu, sering kali terbentang jejaring kolusi, korupsi, dan kongkalikong antara penguasa lokal/nasional dengan korporasi besar. Kepentingan publik dan keselamatan ekologis dikorbankan demi keuntungan segelintir elite. Dalam konteks inilah, kata-kata Mahatma Gandhi yang dikutip dalam buku ini bergema dengan pilu: “Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak untuk memenuhi kerakusan satu orang pun.” Kerakusan inilah yang menggerogoti kedaulatan lingkungan Indonesia. Pemerintah, yang seharusnya menjadi penjaga amanat konstitusi untuk melindungi rakyat dan sumber daya alamnya, justru sering menjadi pihak yang melegalkan perampokan itu melalui regulasi yang pro-investasi jangka pendek tetapi buta terhadap keberlanjutan.
Kritik utama terhadap pemerintah Indonesia adalah inkonsistensi dan ketiadaan visi transformatif yang berani. Di satu sisi, Indonesia aktif menyuarakan komitmen iklim di forum global. Di sisi lain, di dalam negeri, paradigma pembangunan tetap terjebak pada ekstraksi sumber daya alam dan ekonomi ekstraktif. Kebakaran hutan yang berulang, banjir tahunan yang semakin parah, dan konflik agraria adalah gejala dari kegagalan menyeluruh dalam tata kelola lingkungan. The Future We Choose menegaskan bahwa kita tidak bisa lagi menjalankan bisnis seperti biasa. Namun, pemerintah kita masih terjebak dalam “bisnis seperti biasa”, hanya dengan sedikit catatan hijau di laporan tahunan.
Saya tak bermaksud memberikan rekomendasi untuk memecahkan permasalahan yang dialami di Indonesia sebagaimana tertulis diatas, namun lebih kepada beberapa pemikiran untuk generasi mendatang (karena saya sudah tidak percaya lagi pada para generasi tua, para pemimpin politik, DPR dan sebagian besar orang di pemerintahan):
- Revolusi Mental Kebijakan: generasi mendatang harus mengadopsi “Pikiran untuk Bertindak” Figueres dan Rivett-Carnac, terutama Ketabahan (Stubbornness) untuk menolak tekanan korporasi perusak lingkungan, dan Vision (Visi) yang melampaui periode jabatan. Setiap kebijakan harus lulus uji “Dampak 2050”: akankah kebijakan ini membawa kita ke dunia 3°C atau 1.5°C?
- Penegakan Hukum yang Nirmiliteristik dan Transparan: Hukum lingkungan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, terutama terhadap korporasi besar. Sistem perizinan harus dibuat transparan secara daring (one-map policy yang benar-benar dijalankan) dengan partisipasi masyarakat. Korupsi di sektor sumber daya alam harus ditindak sebagai kejahatan luar biasa.
- Transisi dari Ekonomi Ekstraktif ke Restoratif: Alih-alih memberi izin baru untuk sawit dan tambang, insentif besar-besaran harus dialihkan ke ekonomi restoratif: agroforestri, ekowisata berbasis masyarakat, energi terbarukan (surya, bayu, panas bumi), dan industri hijau. Program perhutanan sosial harus diperkuat sebagai model pemberdayaan sekaligus perlindungan.
- Pemberdayaan Masyarakat sebagai Penjaga: Masyarakat adat dan lokal yang hidupnya tergantung pada hutan yang sehat adalah sekutu terbaik dalam pelestarian. Berikan mereka kepastian hukum atas wilayah adat dan libatkan mereka sebagai mitra dalam pengawasan dan restorasi.
- Narasi Baru tentang Kemajuan: Kita perlu mengubah narasi bahwa kemajuan identik dengan alih fungsi lahan. Kemakmuran sejati terletak pada udara bersih, air jernih, ketahanan pangan, dan masyarakat yang sehat—semua hal yang disediakan oleh ekosistem yang lestari.
Apa yang tertuang dalam buku The Future We Choose menurut saya penting, mendesak, dan sangat personal bagi Indonesia. Ia mengingatkan kita bahwa masa depan bukanlah takdir yang pasif kita terima, tetapi sebuah pilihan aktif yang kita buat hari ini melalui kebijakan, investasi, dan suara kita. Banjir di Sumatera semoga saja menjadi alarm terakhir dari alam. Kita bisa memilih untuk menekan tombol tunda dan terus membiarkan kolusi serta kerakusan menghancurkan warisan anak cucu. Atau, kita bisa memilih jalan yang lebih sulit namun mulia: mengutamakan keberanian atas ketakutan, keadilan atas ketamakan, dan kehidupan atas kehancuran. Buku ini adalah seruan untuk memilih yang terakhir. Masa depan Indonesia—apakah akan tenggelam atau tegak—tergantung pada pilihan yang kita buat dalam beberapa tahun ke depan. Waktunya untuk memilih adalah sekarang. (*)