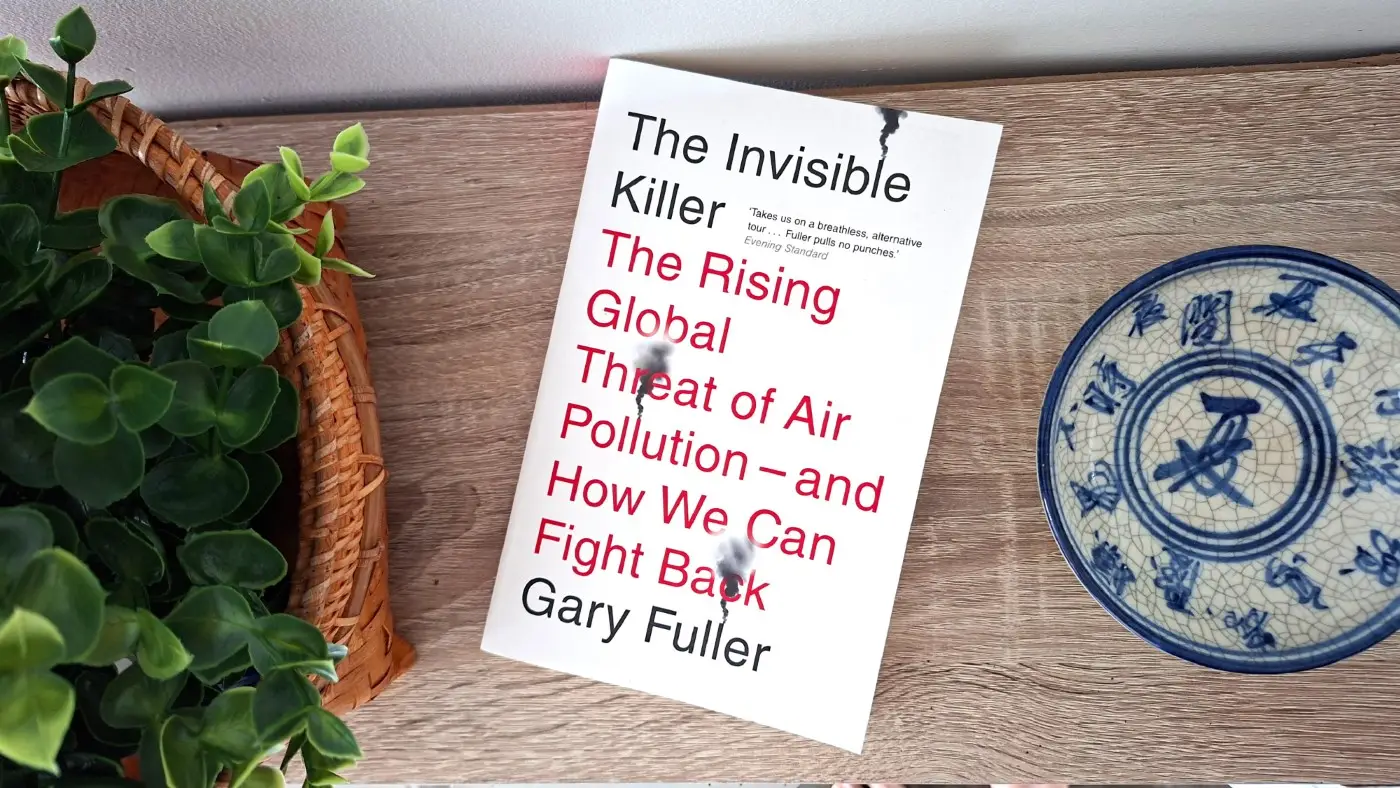Setiap pagi, jutaan warga Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia menghirup sarapan beracun. Bukan dari makanan, tetapi dari polusi udara. Kita telah menerima polusi udara sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan urban, sebuah “trade-off” yang harus ditanggung demi pembangunan.
Kabut kecokelatan yang menyelimuti gedung-gedung tinggi, bau asap knalpot yang menusuk di perempatan lampu merah, dan laporan aplikasi kualitas udara yang terus-menerus menampilkan status “Tidak Sehat”—itulah realitas harian kita. Namun, dalam buku The Invisible Killer: The Rising Global Threat of Air Pollution – and How We Can Fight Back, Gary Fuller, seorang ilmuwan udara terkemuka, membongkar ilusi berbahaya ini. Dengan lugas dan didukung data puluhan tahun, Fuller menunjukkan bahwa polusi udara bukanlah gangguan sampingan, melainkan “pembunuh tak kasat mata” yang merampas jutaan nyawa setiap tahun, menggerogoti ekonomi, dan memperdalam ketidakadilan sosial.
Buku ini adalah tamparan keras sekaligus panduan penting bagi Indonesia, di mana romansa dengan kendaraan bermotor dan pembangunan yang abai terhadap ekologi telah membuat kita menjadi tawanan udara busuk kita sendiri.
Fuller, dengan narasi yang mengalir seperti thriller ilmiah, membawa pembaca dalam perjalanan panjang sejarah polusi udara—dari kabut asap mematikan di London era industri hingga krisis modern di kota-kota Asia. Menurut saya, buku ini mampu menjembatani sains yang kompleks dengan cerita manusia yang menyentuh. Ia tidak hanya memaparkan molekul PM2.5 atau NOx, tetapi juga menjelaskan bagaimana partikel-partikel halus itu menyusup ke aliran darah, merusak organ, memicu stroke, kanker paru-paru, hingga memperburuk kesehatan mental. Fuller dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah krisis kesehatan publik terbesar di dunia, yang membunuh lebih banyak orang daripada malaria, HIV/AIDS, dan perang sekaligus. Ia juga mengurai politik di balik polusi: bagaimana industri mobil, bahan bakar fosil, dan bahkan kebijakan pemerintah yang keliru telah memperpanjang krisis ini.
Di sinilah konteks Indonesia menjadi sangat relevan dan tragis. Perilaku masyarakat Indonesia, khususnya di perkotaan, yang menjadikan kendaraan pribadi (terutama motor) sebagai simbol mobilitas, kemandirian, dan status, telah menciptakan sebuah paradoks. Kendaraan yang seharusnya membawa kemudahan justru menghasilkan kemacetan kronis dan kubangan polusi. Budaya “door-to-door” yang nyaman, didukung oleh infrastruktur transportasi umum yang seringkali tidak nyaman, tidak terintegrasi, dan tidak reliabel, semakin mengukuhkan ketergantungan ini. Kota-kota kita dirancang untuk kendaraan, bukan untuk manusia. Bayangkan, jika Anda bekerja di kawasan Jalan Thamrin, dan rumah Anda di Ciledug. Anda butuh upaya ekstra untuk mencapai kantor tiap hari. Anda harus berganti moda transport beberapa kali, dan berjejalan di dalam busway, MRT atau KRL, dan disambung lagi dengan ojek online untuk merapat ke halte atau stasiun terdekat.
Seperti yang diilustrasikan Fuller dalam konteks global, pilihan individual ini diperkuat oleh sistem yang gagal: uji emisi yang formalistis, bahan bakar dengan standar rendah (perbedaan harga Pertalite dan Pertamax adalah contoh nyata), dan industri otomotif yang gencar memasarkan kendaraan tanpa edukasi dampak kolektifnya.
Lebih dalam lagi, “The Invisible Killer” menyoroti ketidakadilan polusi udara. Mereka yang paling rentan—anak-anak, lansia, komunitas miskin yang tinggal di pinggir jalan raya—merupakan pihak yang paling menderita, meski kontribusi mereka terhadap polusi seringkali paling kecil. Di Jakarta, ini terlihat jelas: para pekerja yang harus menghabiskan berjam-jam di jalan menjadi korban utama, sementara solusi seperti pemurni udara mahal hanya terjangkau oleh segelintir orang. Fuller menegaskan bahwa polusi udara adalah isu demokrasi dan keadilan, persis seperti yang kita alami.
Lantas, adakah perbaikan kedepan untuk pengurangan polusi? Fuller memberikan beberapa solusi:
- Revolusi Data dan Transparansi: Langkah pertama melawan musuh tak kasat mata adalah membuatnya terlihat. Pemerintah daerah harus memperbanyak dan mempublikasikan data pemantauan kualitas udara (PM2.5, NO2, O3) secara real-time, mudah diakses, dan dipahami publik. Data adalah senjata untuk membangun kesadaran dan mendorong akuntabilitas.
- Transformasi Radikal Sistem Transportasi: Kita tidak bisa lagi setengah-setengah. Investasi besar harus dialihkan dari pembangunan jalan (yang justru mendorong lebih banyak kendaraan) ke transportasi umum massal yang terintegrasi, nyaman, dan terjangkau. Integrasi MRT, LRT, TransJakarta, dan kereta komuter dengan feeder bus atau mikromobilitas (sepeda, sepeda listrik) adalah keharusan. Zonasi bebas kendaraan pribadi di pusat kota dan penerapan kebijakan “Superblocks” (seperti di Barcelona) yang memprioritaskan pejalan kaki dan ruang hijau harus bisa menjadi alternatif yang layak dicoba.
- Regulasi yang Berani dan Konsisten: Pemerintah pusat dan daerah harus berani menaikkan standar kualitas bahan bakar ke level Euro 5/6, memperketat dan memaksakan uji emisi berkala yang sesungguhnya (bukan sekadar formalitas), serta mempercepat transisi ke kendaraan listrik dengan menyediakan infrastruktur pendukung dan insentif yang tepat sasaran. Namun, transisi ke listrik hanya bermakna jika sumber listriknya juga bersih (dari energi terbarukan, bukan PLTU batubara). Percuma saja mendorong orang beli kendaraan listrik, kalau untuk mengisi baterainya masih berasal dari listrik berbahan baku fosil.
- Redesain Kota Berbasis Manusia dan Alam: Pembangunan kota harus mengutamakan ruang hijau dan biru. Penanaman pohon pelindung jalan yang tepat jenis (yang menyerap polutan, bukan sekadar peneduh), pembuatan taman kota, dan restorasi sungai dapat menjadi “paru-paru” dan filter alami. Kebijakan tata ruang harus membatasi urban sprawl dan menciptakan kota yang kompak, sehingga orang bisa berjalan kaki atau bersepeda dengan aman dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan harian.
- Pemberdayaan Masyarakat sebagai Agen Perubahan: Kampanye kesadaran harus dilakukan secara masif. Masyarakat perlu diedukasi bahwa mematikan mesin saat berhenti (anti-idling), menggunakan transportasi umum, atau bersepeda adalah aksi nyata penyelamatan nyawa. Tekanan publik dari masyarakat yang terinformasi adalah kekuatan terbesar untuk mendorong perubahan kebijakan.
Kesimpulannya, buku ini dengan jelas menunjukkan bahwa udara bersih bukanlah kemewahan, melainkan hak asasi manusia. Untuk Indonesia, khususnya Jakarta dan kota besar lain, membaca buku ini harus disertai dengan rasa urgensi yang mendalam. Kita sedang membiarkan generasi sekarang dan mendatang menghirup koktail beracun setiap hari. Solusinya ada, dan sebagian besar telah teruji di berbagai belahan dunia. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian politik untuk melawan bisnis seperti biasa, visi jangka panjang untuk membangun kota yang layak huni, dan komitmen kolektif untuk mengubah perilaku.
Apakah ini realistis untuk diwujudkan di Indonesia? Rasanya harus menunggu rezim berganti (yang belum tentu menjamin akan ada perubahan juga). Bersabarlah empat tahun lagi. (*)