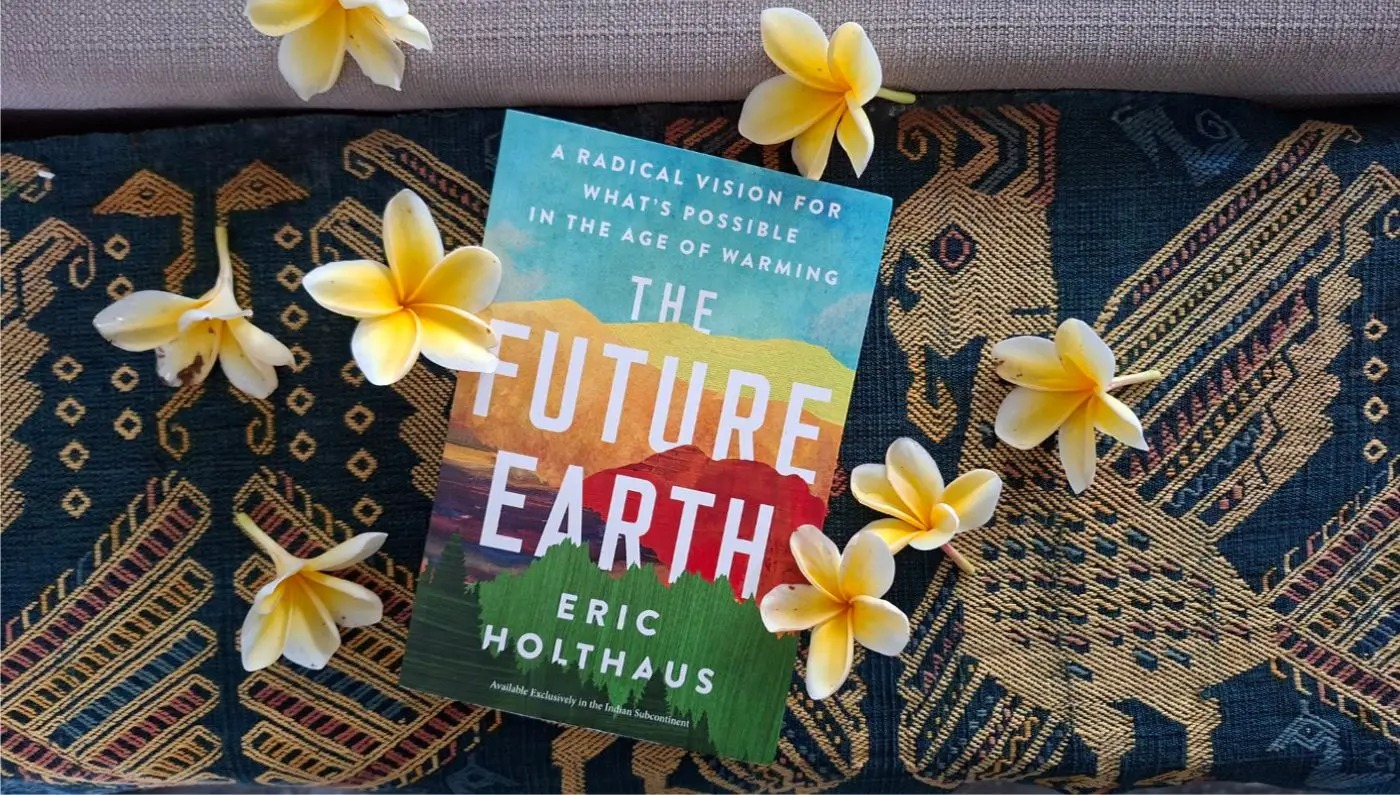Indonesia adalah raksasa karbon yang terjaga. Dari kebakaran gambut di Kalimantan yang menghembuskan asap hingga ke negara tetangga, hingga PLTU batubara yang menyumbang lebih dari 60% energi nasional, jejak emisi gas rumah kaca kita menghitamkan atmosfer dan masa depan.
Dalam tenggat waktu yang semakin menipis untuk menghindari bencana iklim terburuk, Eric Holthaus, dalam bukunya yang visioner dan personal “The Future Earth: A Radical Vision for What’s Possible in the Age of Warming”, menawarkan sesuatu yang jarang kita temui: optimisme yang radikal. Bukan optimisme naif, tetapi optimisme yang bekerja, yang dibangun di atas sains keras, imajinasi sosial yang luas, dan keyakinan bahwa kita masih bisa—bahkan harus—membayangkan dan membangun masa depan yang layak dihuni. Buku ini menjadi cermin sekaligus tantangan telak bagi Indonesia, yang janji pengurangan emisinya masih terperangkap antara retorika hijau di kancah global dan realitas ketergantungan pada ekonomi ekstraktif di dalam negeri.
Holthaus, seorang jurnalis iklim, membawa pembaca dalam perjalanan unik. Sebuah narasi jurnalistik dari masa depan. Dia “mewawancarai” sejarah dari tahun 2020 hingga 2050, merangkai laporan-laporan fiksi namun ilmiah tentang bagaimana dunia berhasil menghindari titik kritis iklim. Menurut saya, buku ini melampaui narasi “kiamat” yang melumpuhkan (doomism), dan menggantinya dengan peta jalan naratif yang konkret. Dia tidak hanya mengatakan “kita harus mengurangi emisi,” tetapi menggambarkan seperti apa masyarakat pada tahun 2030 yang telah melarang iklan mobil bahan bakar fosil, atau pada tahun 2045 di mana pertanian regeneratif telah menjadi arus utama. Holthaus berargumen bahwa untuk menyelesaikan krisis, kita pertama-tama harus mampu membayangkannya telah terselesaikan. Semacam imajinasi kolektif yang sebenarnya kita butuhkan.
Seperti saat membaca buku-buku lainnya, saya mengaitkan The Future Earth ini dengan konteks Indonesia. Hasilnya adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, Indonesia memiliki komitmen global yang ambisius: mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, dan mengklaim pengurangan emisi 31,89% dengan upaya sendiri pada 2030. Kebijakan seperti pengembangan energi terbarukan, moratorium hutan, dan program biodiesel (B35) kerap diangkat.
Namun, di sisi lain, realitas kebijakan di lapangan sering kali kontradiktif. Rencana besar “Carbon Capture and Storage” (CCS) untuk ladang-ladang minyak dan gas tua justru berpotensi menjadi dalih untuk memperpanjang umur industri fosil, alih-alih menghentikannya secara bertahap. Ironi ini mencapai puncak absurditasnya dalam COP30 di Brasil (10-21 November 2025). Konferensi iklim paling penting yang diadakan di jantung Amazon ini, sayangnya, mulai diwarnai oleh keterlibatan sponsor dan mitra dari perusahaan minyak dan gas raksasa. Sebagai salah satu negara pemilik hutan hujan tropis terbesar, menurut saya, kehadiran Indonesia di event ini seperti kehilangan momentum dan hanya menjadi peserta pasif. Event ini serasa telah dibajak oleh kepentingan industri penyebab krisis dan menjadi bagian dari greenwashing skala global.
Diplomasi iklim Indonesia saat ini terjebak dalam logika kompromi yang berbahaya. Kita datang ke meja perundingan dengan cap “penjaga hutan” sambil terus mengizinkan perluasan perkebunan dan tambang di wilayah yang kritis. Kita membawa biodiesel sebagai solusi, sambil mengabaikan bahwa produksinya masih sering dikaitkan dengan deforestasi. Dan yang paling mengkhawatirkan, kita mungkin melihat keterlibatan perusahaan fosil dalam COP30 sebagai “peluang bisnis” untuk proyek CCS atau perdagangan karbon, ketimbang sebagai konflik kepentingan yang fundamental yang merusak integritas proses iklim itu sendiri. Partisipasi Indonesia di COP30 pada akhirnya menjadi pameran dagang untuk solusi semu.
Daripada terus menerus mengumpat kepada Pemerintah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan kedepan, dalam skala Negara. Ini bukan rekomendasi (karena menurut saya Pemerintah sekarang tak butuh masukan dan rekomendasi. Mereka asik dengan agendanya sendiri), hanya sekedar catatan saja, sebagai penanda nantinya apakah dalam lima tahun kedepan ada kemajuan yang dibuat oleh Negara.
Pertama, Berpikir dalam Skala Sistem. Indonesia harus berhenti melihat pengurangan emisi sebagai daftar proyek yang terpisah-pisah (proyek energi surya di sini, program penanaman di sana). Kita perlu visi sistemik holistik ala Holthaus: merombak total sistem energi, transportasi, pangan, dan tata ruang secara terintegrasi. Transisi energi harus berarti phase-out batubara yang terencana dan adil, bukan sekadar co-firing yang memperpanjang usia PLTU.
Kedua, Memimpin dengan Keadilan, Bukan Kompromi: Sebagai salah satu negara “besar” di Kawasan ASEAN dan kekuatan Global South, Indonesia harus menggunakan panggung internasional untuk mengadvokasi keadilan iklim dengan suara lantang. Ini berarti menuntut pendanaan iklim yang nyata dari negara maju, menolak solusi palsu seperti offset karbon yang mengabaikan hak masyarakat adat, dan membersihkan delegasinya dari kepentingan perusahaan fosil. Diplomasi iklim harus tentang penyelamatan bumi, bukan negosiasi bisnis.
Ketiga, Menginvestasikan Imajinasi Sosial: Pemerintah dan masyarakat sipil perlu membangun narasi masa depan Indonesia yang positif pasca-fosil. Seperti yang dilakukan Holthaus, kita perlu membuat cerita yang menarik tentang Indonesia di tahun 2045: negara dengan kota-kota yang dipenuhi transportasi umum listrik dan ruang hijau, desa-desa yang mandiri energi surya, dan ekonomi yang digerakkan oleh industri kreatif dan pertanian regeneratif yang menghidupkan, bukan membunuh, tanah. Narasi ini harus lebih kuat dari narasi “pertumbuhan melalui ekstraksi”.
Yang terakhir, Mengakui dan Memperbaiki Paradoks Kebijakan: Moratorium harus menjadi larangan permanen. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat harus menjadi prioritas utama, karena mereka adalah penjaga hutan terbaik. Setiap kebijakan harus diuji dengan pertanyaan: Apakah ini membawa kita lebih dekat ke “Future Earth” yang diidamkan, atau hanya mempercantik status quo yang merusak?
Setelah selesai membacanya, saya merasa buku ini seperti membebaskan dan menuntut. Ia membebaskan kita dari belenggu keputusasaan, tetapi menuntut keberanian untuk berimajinasi dan bertindak secara radikal. Bagi Indonesia, buku ini adalah wejangan: kita tidak bisa lagi duduk di dua kursi. Pilihan antara membela kehidupan atau memperpanjang agenda industri fosil harus dibuat sekarang.
Masa depan bumi—dan masa depan Nusantara—tergantung pada jawaban kita atas pertanyaan itu.
Waktunya untuk berimajinasi, lalu beraksi.